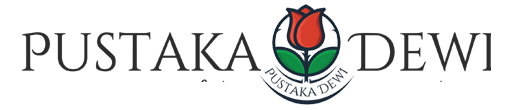Malam ini takseperti malam-malam biasanya. Entah mengapa bisa terjadi? Seorang pemuda seperempat abad bergumam duduk termenung di atas bantaran sungai dekat tempat ia mengais rezeki. Bintang-gemintang takramah menampakkan wajahnya beberapa malam ini. Hanya riak arus sungai yang masih setia menemani lamunan sang pemuda sebagai ujung penghibur dikala letih. Walau sesekali buntalan-buntalan plastik sampah hanyut di sana. "Uh, muak aku melihat semua ini. Ibu kota macam apa ini? Tak-ada yang bisa dibanggakan sungainya."
Sebotol minuman soda ia tenggakkan kembali untuk yang ke-tiga kalinya, hingga setengah botol yang bersisa. Sambil sesekali ia menendang-nendang batu kerikil ke tengah sungai, bak pemain bola yang sedang berlatih tendangan jarak jauh. "Kenapa dengan semua ini?" Tanyanya resah sambil menarik napas dan menghembuskannya kembali.
Gedung-gedung bertingkat masih berdiri angkuh berjajar di hadapannya. Lampu-lampu itu begitu mewah terpandang dari sudut mata pemuda ini. Kemudian menenggak kembali botol digenggamannya dan menghabiskannya. Meremasnya. Berteriak dalam batin, "Ya, Tuhan ada apa denganku?"
Adib. Ya, pemuda seperempat abad ini bernama Adib Saeful Rizal. Ia berasal dari sebuah kampung cukup terpencil dan jauh dari akses jalan. Apabila ia membandingkan fasilitas sarana umum di hadapannya kini dengan kampungnya sungguh seperti 'bumi dan langit'. Listrik pun belum masuk di sana, jalan-jalan sudah cukup nyaman bagi penduduk setempat yang hanya terbuat dari jejeran batu hasil swadaya masyarakat tanpa lapisan aspal hitam mulus. Teve? Jangan kau tanya soal alat elektronik macam di ibu kota. Di sana barang mewah dan canggih hanyalah radio bertenaga bantu batu baterai. Dan itu hanya Pak Haji Sobur yang memilikinya, juragan kayu.
"Tuhan hamba belum dapat membahagiakan orang tua hamba." Untaian do'a terlantun lirih dan berbisik. Memang gaji seorang kuli bangunan belum dapat mencukupi kebutuhan hidup Adib dan orang tuanya di kampung.
Riak sungai masih bergemecik deras seperti biasanya.
Tubuh lelahnya pun ia sandarkan di atas kasur dalam ruang indekos yang ia sewa tiga bulan lalu dengan harga amat murah. Ia pandangi langit-langit kamar sewaannya. Tiba-tiba terlihat seburat cahaya rekaman semua kenangan di masa lalu bersama Ambu. "Ambu.... Ambu.... tangan adib sudah bisa pegang telinga." Celoteh Adib kecil girang sambil menunjukkan tangannya yang menggapai daun telinganya.
"Subhanallah, Adib sudah besar ya. Sudah boleh sekolah. Nanti Ambu hantar daftar ke sekolah, ya nak." Ambu tersenyum lembut. Adib kecil tersenyum girang terlihat dari matanya yang berbinar.
Keesokkan harinya Adib kecil pun bergegas mendaftar sekolah pertamanya sambil bergandengan tangan bersama Ambu, tersenyum-senyum girang. Sungguh indah saat-saat itu.
Cahaya itu meredup kemudian menghitam pekat dan seolah terputar kembali kenangan Adib ketika masih menjadi remaja tanggung, saat menjelang masuk ke Sekolah Menengah Pertamanya. "Ambu, terima kasih."
"Sama-sama, ini sudah kewajiban Ambu, Dib." Ambu tersenyum hangat sambil merapihkan kerah putih seragam putih-biru pertama Adib. Senyum pemuda tanggung itu pun mengembang.
"TIDAK JANGAN MEREDUP!!!" Sahut Adib setengah menggertak takrela suasana indahnya bersama Ambu menghilang.
Cahaya itu kembali redup dan gelap pekat. Cahaya itu takkan kembali bersinar. Senyum lembut Ambu taknampak jelas lagi. Sentuhan tangan saat menggenggam Adib kecil dan Adib remaja tanggung pun takkembali terasa. Kemana semua itu menghilang?
Adib seorang diri menggali lamunannya sendiri. Malam itu ia kembali menghampiri bantaran sungai untuk yang ke-dua kalinya. Tempat paling nyaman baginya. Kembali ia mengingat-ingat semua kejadian itu. Ya, kejadian sore itu.
Sore dimana Ambu berada di sungai sedang membersihkan belanjaannya selepas pagi tadi. Tiga kilo ikan bandeng menjadi menu spesial makan malam. Ya, spesial karena siang tadi mendapat berita yang sangat bahagia dari putra semata wayangnya. "Dib, tolong bantu Ambu, nak."
Saat itu di rumah, Adib tengah asik menatap angka-angka yang tersemat di buku rapotnya. Ia tersenyum-senyum kecil melihat indah rapotnya. Walau yang ada hanya angka enam yang terbalik tersemat di sana. Bila harus mengingat-ingat kejadian siang tadi, saat Pak Engkos memanggil namanya di awal sebelum teman-temannya sekelas, itu amat membanggakan. Karenanya Adib kembali dinobatkan menjadi langganan juara umum yang belum dapat direbut oleh temannya sekelas.
Entah mengapa saat itu tiba-tiba hujan deras. Ambu terbawa hanyut air bah bersama menu makan malam spesial keluarganya dan do'a-do'a untuk Adib, putranya. Teriakkan minta tolongnya pun sia-sia, tenggelam bersama senyum hangatnya.
"Dib, Ambu. Ambu, Dib!" Abah tersekat selepas tahu istrinya tak-ditemukan di sungai.
"AMBUUUU...." Teriak Adib histeris. Lututnya lemas, tersungkur hingga membiarkan alur sungai kesedihan mengalir deras dari sudut matanya.
Adib terpukul. Adib gamang. Terlebih Abah. Takkan ada lagi senyum hangat, lembut genggaman saat ketika Adib kecil dan Adib remaja tanggung dihantarkan masuk sekolah. Tak-akan ada yang menghantarkan seperti itu nanti kelak Adib masuk Sekolah Menengah Atasnya.
Pemuda ini menghela napas panjang untuk kenangan itu. Ia pun terduduk di atas batu besar dekat bantaran sungai. Hingga kini sungai menjadi tempat pelepas rindunya kepada Ambu semata wayangnya. Ibu yang senantiasa menghatarkannya dengan senyuman hangat dan sentuhan genggaman yang lembut itu. Walau sungai Ibu kota tak-sebersih di kampungnya.
Adib -tertunduk dalam- di antara hanyutnya sampah-sampah ibu kota, laiknya seseorang takzim mengunjungi pusara.[]