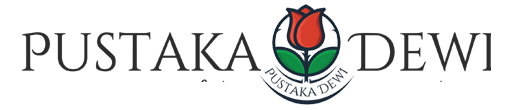“Terminal Kampung Rambutan”, begitulah nama tempat tujuan saya tersemat dengan apik di salah satu papan penunjuk arah berwarna dasar hijau itu. Saya rasa inilah Jakarta di 18.30 Pm. Papan itu semakin menghilang dari pelupuk mata ditikungan tajam arah terminal yang dimaksud. Bus antar kota yang saya naiki ini semakin menurunkan kecepatannya disekitar 20 km/jam. Saya yakinkan lagi keberadaan saya ini dalam hati, kini saya disini. Benar kawan saya disini, Jakarta yang amat kalut.
Perlahan saya coba turun dari bus dan menginjakkan kaki di kota ini. Sungguh amat tinggi intensitas mobilisasi mereka. Lihat saja di sekeliling saya, kawan. Mereka gemar sekali mengenakan masker yang melekat rapat menutupi setengah wajahnya, membuat sulit untuk menebak ekspresi saat diajak berbicara. Mereka terbiasa dengan antrian panjang saat sore hari di halte busway. Mereka rela menghibur dirinya dengan membenamkan kedua daun telinganya di head phone mereka. Mereka terbiasa berbicara dengan suara yang harus di lantangkan dan itu lumrah kata mereka karena setiap hari disuguhkan oleh; deru mesin mobil, kelakson kendaran, teriakan penjajak koran dan belum lagi nyanyian pengamen yang silih berganti seperti sudah di jadwal dengan rapih penampilan mereka. Ini sungguh tak biasa bagi seorang pemuda kampung yang mengadu nasib di kota sebesar ini.
Telpon genggam sudah menjerit beberapa kali yang tak sempat terangkat karena deru mesin bus lebih mendominasi. Rupa-rupanya dari sahabat saya yang tinggal disini mencemaskan kondisi pelancong ini yang sedikit meraba-raba arah jalan menuju ke kosannya. Saya mencoba menenangkannya dengan me-sms-nya, “Salam, Sob saya sudah sampai di Rambutan.” Tanpa harus menunggu sms balasannya saya langsung bergegas menuju Bus patas arah Rawamangun Jakarta Timur selepas menunaikan shalat Maghrib.
Selang tiga puluh menit, akhirnya sampai didepan halte busway Sunan Giri. Saya transit tepat didepan salah satu toko baju busana muslim. “Ana dah sampai di Rabb*** nih.”, Kabar ku kirim via sms. Sms balasan darinya saya terima lima menit kemudia, “Ok, ana kesana. Tunggu sebentar yah? ana masih di jalan dari ITC.”
Sebotol minuman softdrink sudah habis kering kerontang di lima belas menit penantian. Apalah yang bisa dilakukan bagi seorang perantau yang buta arah ini. Maka terdiam membatu dengan mencoba terlihat santai di mata para pejalan kaki lain. Duduk-duduk di pembatas pagar yang rendah sedengkul orang dewasa di depan toko itu, sambil menurunkan tensi kepanikan yang merongrong di benak; Salah tempatlah, bukan halte ini tempat berhentinya, bukan sunan giri tapi sunan gunung jati nama lokasinya, bla-bla dan bla-bla. Tumpah ruah semua prasangka buruk. Ada seorang tukang ojeg yang perangainya lebih cocok sebagai pereman seperti melihati. Semakin menjadi-jadi saja semua prasangaka tadi ke arah kriminal.
“wush........ wush...........” Angin kencang menyapu bahu-bahu jalan termasuk -si perantau buta arah- ini. Kemudian di susul hujan besar yang mengancam dengan kilat-kilat petirnya. Di tengah gelapnya malam dan hujan deras muncul sesosok yang sepertinya saya kenal dari bus metromini nomor 3 itu. Nampaknya ia menuju tempat saya berteduh. “Akhirnya sampai juga ente, Fit?” tanya dia. “Iya, ana udah di Jakarta, sob.” jawab saya.
Tanpa berlama-lama berteduh karena hujan telah reda, walau gemercik rintik hujan menghiasi langkah kami menuju kosan. Dan sesampai dikamar 4x3 m-nya, saya hanya bisa terdampar di pulau kecil nyaman yang orang-orang bilang itu kasur. Saya lewati malam dengan tidur pulas tuk mengobati lelah yang meradang ke ubun-ubun, tentunya setelah melaksanakan shalat Isya di 22.00 Pm. “Selamat tidur, kawan....”[]
Copyright © All Rights Reserved / Designed By: Templatezy