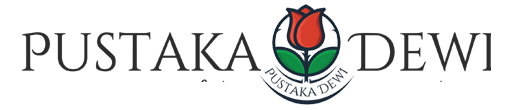Alkisah ini berawal dari sebuah pertemuan yang tak-disangka-sangka. Ketika ketidaksengajaan seseorang menabrakku di sebuah stasiun tempat biasa aku memburu kereta listrik pagi buta demi absensi yang takpernah telat. Ya mesin scaner itu selalu men-scan jemariku demi upah yang tak-terpotong. Pagi itu entah mengapa aku bisa bertabrakkan dengan seorang pemuda seperempat abad. Nampaknya aku tak-terburu-buru karena rutinitas ini membuatku terlatih.
"Maaf Mba, saya buru-buru." Dengan wajah memelas ia pun meminta maaf.
"Iya, gak apa-apa." Jawabku tersenyum sambil mengambil tas jinjingku yang sempat terjatuh. Pertemuan itu begitu singkat sekali. Hanya sesederhana itu saja. Tak-ada tanya nama atau alamat, bahkan nomor telepon. Ah, hal seperti itu hanya ada dalam sinetron saja.
Kami pun bergegas menuju gerbong kereta masing-masing. Jalur Jakarta yang aku tunggangi. Pemuda itu telah lenyap dikeramaian gerbong lainnya.
Pekerjaanku sebagai karyawati di sebuah bank terkemuka di negeri ini menuntutku harus tetap gesit dan cekatan. Teller, itu dia profesiku kini. Pekerjaan yang aku lamar tiga bulan yang lalu. Tentunya penampilan yang anggun dan elegan menjadi standarku saat ini. Tapi itu berlaku ketika sudah sampai di kantor. Kalau untuk sekedar menyeberangi satu gerbong ke gerbong yang lain rasa-rasanya takperlu berpenampilan berlebihan. Cukup saja dengan berpakaian santai tapi sopan. Bagiku cukup.
***
Sesampainya di kantor,
"Pagi Mba Ratna." Tegur ramah Pak Nurdin, salah-satu security yang cukup senior di kantor. Sambil membukakan pintu
"Pagi Pak. Bagaimana kabarnya, Pak Nur?"
"Baik Mba. Kalau Mba sendiri bagaimana?" Masih dengan keramahannya Pak Nur kembali bertanya.
"Oh, baik sekali Pak. Selamat bertugas Pak."
"Sama-sama Mba. Semoga betah ya Mba."
Aku pun berlalu dengan riang meninggalkan Pak Nurdin yang ramah itu di tempatnya ia bertugas. Tentunya aku bergegas membereskan meja kerjaku yang lebih tepatnya meja stand kami. Meja kami. Meja kerja Lona dan aku.
"Pagi Say." Lona dengan senyum lesung pipitnya itu menyapa.
"Pagi Cantik."
"Terima kasih, Cantik." Begitu Lona, selalu saja bisa membalas pujianku dengan pujiannya.
Hari ini nasabah kami begitu padat. Maklum di tanggal tua banyak sekali transaksi. Setoran atau pun tarik setoran. Entahlah, hanya mereka dan Tuhan yang tahu mau diapakan semua uang mereka. Uang mereka hak mereka tentunya. Kami hanya sekedar melayani dengan se-prima mungkin. Walau aku dan Lona masih dalam tahap masa percobaan. Tapi bagiku dan Lona ini sudah bukan perkara yang sulit. Kami terbilang karyawati yang cepat belajar.
Tiga bulan terakhir ini kami sudah seperti sahabat yang lama kenal. Lona kini menjadi sahabatku yang baik dan cantik. Kami selalu menghabiskan waktu kami dengan bersama-sama. Seperti makan siang, belanja jika kami mampu, dan berangkat liburan akhir pekan sekaligus akhir bulan ketempat-tempat wisata di Jakarta. Bulan kemarin kami jalan-jalan ke Kebun Binatang Ragunan.
"Sudah puas kan ngejenguk paman kamu, Na?"
"Paman apa?" Tanyaku heran.
"Itu tuh, Orang Utan." Lona memasang wajah menyeringainya yang menyebalkan, bikin hati dongkol. Tapi ia pandai mengambil hati orang. Lihat saja selepas keusilannya itu ia tawarkan suasana dengan mentraktir semangkuk makanan favoritku, baso.
Begitu kebersamaan kami selama tiga bulan terakhir. Menyenangkan, saling mengakrabkan, dan tentunya selalu hangat dengan candaan kami.
Terkhusus hari ini, Lona dan aku begitu sibuk. Tak-ada senyuman pagi tadi. Kini yang ada hanya wajah-wajah serius terpasang di kami. Walau sekali lagi aku bilang, kami terbilang yang cepat dalam menyesuaikan diri soal pekerjaan.
Saat jam istirahat tiba di kantin belakang lona pun berujar, "Lumayan juga hari ini." Sambil mengusap-usap keningnya yang berkeringat.
"Bukan lumayan lagi Lon. Ini seperti artis kebanjiran penggemar yang memburu tanda tangan kita." Aku pun duduk di sampingnya sambil membawa pesanan kami berdua.
"Hahaha, artis. Boleh juga perumpamaannya." Terkekeh-kekeh Lona menyambut guyonanku.
Habis sudah pesanan makan siang kami. Tandas sudah piring-piring kami tak-bersisa, kecuali tulang-belulang ayam goreng nasi timbel yang mudah-mudahan sejuta tahun lagi akan menjadi fosil berharga. Lona selepas makan izin sebentar ke toilet sambil membawa smart phone-nya yang berdering. Aku masih terduduk di meja favorit makan siang kami, pojokkan sebelah kanan dekat jendela berpemandangan Jakarta. Sungguh sibuk kota ini. Aku pun terkadang sempat berpikir, sungguh beruntungnya aku dapat mencicipi kehidupan di kota sebesar ini dan sudah memiliki status kerja yang jelas.
Selang lima menit Lona pun menghampiriku dengan wajah sedikit murung. "Kenapa kamu cantik?" Empatiku mencoba menghiburnya.
"Nggak pa-pa, yuk." Ajaknya dengan lemas.
Aku pun menghampirinya dengan rasa yang tak tentu. Sebagai teman dan patner kerja aku harus dapat menjadi teman berbagi baginya. "Ada yang mau diceritakan. Lon?"
"Nanti saja selepas kita pulang." Jawabnya singkat.
Suasana kerja kami pun tak seperti biasanya. Walau senyum Lona mengembang setiap kali melayani nasabah, aku yakin hatinya masih sedih. Biarlah, nanti sepulang kerja saja aku membahasnya.
Tepat pukul 19.00, kami pun bergegas siap-siap untuk pulang. Aku pun menghampiri Lona yang masih termenung, "Cantik kenapa?"
Lona pun membenamkan wajahnya di pundakku sambil menumpahkan butir-butir kesedihan dari sudut matanya.
"Kenapa Cantik? Ada apa?" Tanyaku mencoba menenangkannya.
"Brian, Na. Dia ja-hat." Ujarnya dengan tercekat ingus dan tangisannya.
"Siapa Brian? Pacarmu, Cantik?"
Ia pun mengangguk pelan. Kemudian mengelapi hidungnya yang basah dengan tisu pemberianku.
"Oh, kenapa dengan dia?"
"Aku minta putus lewat telepon siang tadi di kantin."
"Loh, kamu yang minta putus, kok, kamu yang nangis?"
"Abis dia bikin sebel."
"Sebel gimana?"
"Sebel soal beberapa hari terakhir ini dia susah sekali dihubungi. Setiap janjian selalu dibatalkan mendadak. Makanya tadi dia nelpon mau ngejelasin semuanya. Alasannya kantor tempat dia kerja menugaskannya untuk lembur. Tapi aku gak terima kalau urusan kerjaan dijadikan alasannya. Kan, dia bisa bilang dari jauh-jauh hari, terkesan dibuat-buatnya. Aku pokoknya sebel banget, Na.
"Apa memang semua cowok seperti itu ya, Na? Aku dengan Brian sudah jalan lima tahun, semenjak kuliah dulu sampai sekarang. Bahkan dia membatalkan pertemuan hari jadi kita dengan mendadak. Siapa yang gak sebel coba? Kamu kalau diposisi aku harus ngapain, Na?"
Aku sempat kaget dengan kondisi sahabatku ini. Dia begitu lain, meledak-ledak takseceria bisanya. Tukang usil dan pengambil hati orang yang ulung. "Ya, yang sabar Cantik. Aku kalau diposisi kamu ya akan sama sepertimu. Curhat dengan kamu, menangis, dan mungkin mengambil keputusan yang terburu-buru seperti kamu tadi siang, putus.
"Tapi bukankah kamu sudah menjalani ini cukup lama. Lima tahun itu bukan waktu yang singkat, loh. Coba kamu pikirkan kembali masak-masak. Apa lagi cincin yang melingkar di jari manismu itu sudah menjadi komitmen dia ke kamu kan?"
Dengan sedikit sesenggukkan Lona mengangguk, "Terima Kasih, Cantik. Kamu sahabat yang baik. Aku mau pertimbangkan dulu. Apa lagi keluarga besar aku dengan dia sudah saling ketemu dan merestui hubungan kami. Terima kasih ya." Dia pun memelukku dengan senyuman dan lesung pipitnya.
***
Perkara semalam sudah membuat Lona lega sepertinya. Dan pagi ini aku menjalani kembali peranku seperti biasa. Stasiun menjadi tempatku memburu waktu. Lagi-lagi pria seperempat abad itu kembali menabrakku.
"Aduh, maaf Mba. Saya buru-buru." Wajah itu kembali terekam dan memelas.
"Oh, iya gak apa-apa." Jawabku singkat.
"Oh ya, Mba yang kemarin ya? Masih ingat Saya?" Tanyanya mengenaliku.
"Ya. Mas yang tempo hari menabrak saya juga." Sebenarnya ini hanya basa-basi saja, tentunya aku hafal betul dia yang menabrak dan menjatuhkan tas jinjingku.
"Iya Mba. Kenalkan nama saya Brian."
Ya Tuhan, adegan sinetron ini terjadi juga dalam kehidupan nyataku. "Oh ya, saya Ratna."
"Mba Ratna mau kemana?"
"Oh, saya kerja Mas Brian."
"Oh, dikirain saya mau jalan-jalan. Maaf soalnya taknampak seperti yang lainnya. Terlihat santai."
"Iya, saya selalu ganti seragam nanti di kantor."
"Oh begitu. Kalau boleh tahu Mba kerja dimana?"
"Saya kerja disalah satu bank di bilangan Jati Negara."
"Oh gitu, tunangan saya juga kerja disana Mba. Lona namanya."
Ya Tuhan, dunia ini begitu sempit. Aku baru sadar pria inilah yang aku bicarakan dengan Lona semalam. Benar namanya "Brian" aku lupa. Dari perangainya dia sopan. Sepertinya hanya miskomunikasi saja Lona.
"Mba... Mba....?" Tanyanya memecahkan lamunanku.
"Oh ya. Lona Ayunda Putri bukan?" Tanyaku penasaran.
"Iya betul, yang kerja dibagian teller."
"Kalau Lona yang itu sahabat saya. Tepatnya teman semeja kerja dengan saya." Benar sudah ini benar orangnya.
"Wah, gak nyangka ya. Bisa ketemuan di sini. Kalau begitu salam ke Lona ya." Senyumnya sambil berpamitan.
Aku pun hanya bisa melambaikan tangan perkenalan singkat itu sambil memegang smart phone-ku yang telah merekam nomor hand phone-nya. Sungguh takpercaya semua ini bisa terjadi bagai sinetron. Perkenalan nama dan diakhiri saling tukar nomor telepon.
Sesampainya di kantor aku pun mendapati sahabatku Lona sudah berseri kembali. Sudah tentu aku ceritakan perkenalan kami ke Lona. Dan pada akhirnya aku menjadi mediator atau tepatnya juru damai bagi mereka berdua di ujung smart phone-ku. Aku kini menikmati peran baru itu dengan enjoy, demi sahabat dan si pemuda penabrak, Brian.[]
Begitu kebersamaan kami selama tiga bulan terakhir. Menyenangkan, saling mengakrabkan, dan tentunya selalu hangat dengan candaan kami.
Terkhusus hari ini, Lona dan aku begitu sibuk. Tak-ada senyuman pagi tadi. Kini yang ada hanya wajah-wajah serius terpasang di kami. Walau sekali lagi aku bilang, kami terbilang yang cepat dalam menyesuaikan diri soal pekerjaan.
Saat jam istirahat tiba di kantin belakang lona pun berujar, "Lumayan juga hari ini." Sambil mengusap-usap keningnya yang berkeringat.
"Bukan lumayan lagi Lon. Ini seperti artis kebanjiran penggemar yang memburu tanda tangan kita." Aku pun duduk di sampingnya sambil membawa pesanan kami berdua.
"Hahaha, artis. Boleh juga perumpamaannya." Terkekeh-kekeh Lona menyambut guyonanku.
Habis sudah pesanan makan siang kami. Tandas sudah piring-piring kami tak-bersisa, kecuali tulang-belulang ayam goreng nasi timbel yang mudah-mudahan sejuta tahun lagi akan menjadi fosil berharga. Lona selepas makan izin sebentar ke toilet sambil membawa smart phone-nya yang berdering. Aku masih terduduk di meja favorit makan siang kami, pojokkan sebelah kanan dekat jendela berpemandangan Jakarta. Sungguh sibuk kota ini. Aku pun terkadang sempat berpikir, sungguh beruntungnya aku dapat mencicipi kehidupan di kota sebesar ini dan sudah memiliki status kerja yang jelas.
Selang lima menit Lona pun menghampiriku dengan wajah sedikit murung. "Kenapa kamu cantik?" Empatiku mencoba menghiburnya.
"Nggak pa-pa, yuk." Ajaknya dengan lemas.
Aku pun menghampirinya dengan rasa yang tak tentu. Sebagai teman dan patner kerja aku harus dapat menjadi teman berbagi baginya. "Ada yang mau diceritakan. Lon?"
"Nanti saja selepas kita pulang." Jawabnya singkat.
Suasana kerja kami pun tak seperti biasanya. Walau senyum Lona mengembang setiap kali melayani nasabah, aku yakin hatinya masih sedih. Biarlah, nanti sepulang kerja saja aku membahasnya.
Tepat pukul 19.00, kami pun bergegas siap-siap untuk pulang. Aku pun menghampiri Lona yang masih termenung, "Cantik kenapa?"
Lona pun membenamkan wajahnya di pundakku sambil menumpahkan butir-butir kesedihan dari sudut matanya.
"Kenapa Cantik? Ada apa?" Tanyaku mencoba menenangkannya.
"Brian, Na. Dia ja-hat." Ujarnya dengan tercekat ingus dan tangisannya.
"Siapa Brian? Pacarmu, Cantik?"
Ia pun mengangguk pelan. Kemudian mengelapi hidungnya yang basah dengan tisu pemberianku.
"Oh, kenapa dengan dia?"
"Aku minta putus lewat telepon siang tadi di kantin."
"Loh, kamu yang minta putus, kok, kamu yang nangis?"
"Abis dia bikin sebel."
"Sebel gimana?"
"Sebel soal beberapa hari terakhir ini dia susah sekali dihubungi. Setiap janjian selalu dibatalkan mendadak. Makanya tadi dia nelpon mau ngejelasin semuanya. Alasannya kantor tempat dia kerja menugaskannya untuk lembur. Tapi aku gak terima kalau urusan kerjaan dijadikan alasannya. Kan, dia bisa bilang dari jauh-jauh hari, terkesan dibuat-buatnya. Aku pokoknya sebel banget, Na.
"Apa memang semua cowok seperti itu ya, Na? Aku dengan Brian sudah jalan lima tahun, semenjak kuliah dulu sampai sekarang. Bahkan dia membatalkan pertemuan hari jadi kita dengan mendadak. Siapa yang gak sebel coba? Kamu kalau diposisi aku harus ngapain, Na?"
Aku sempat kaget dengan kondisi sahabatku ini. Dia begitu lain, meledak-ledak takseceria bisanya. Tukang usil dan pengambil hati orang yang ulung. "Ya, yang sabar Cantik. Aku kalau diposisi kamu ya akan sama sepertimu. Curhat dengan kamu, menangis, dan mungkin mengambil keputusan yang terburu-buru seperti kamu tadi siang, putus.
"Tapi bukankah kamu sudah menjalani ini cukup lama. Lima tahun itu bukan waktu yang singkat, loh. Coba kamu pikirkan kembali masak-masak. Apa lagi cincin yang melingkar di jari manismu itu sudah menjadi komitmen dia ke kamu kan?"
Dengan sedikit sesenggukkan Lona mengangguk, "Terima Kasih, Cantik. Kamu sahabat yang baik. Aku mau pertimbangkan dulu. Apa lagi keluarga besar aku dengan dia sudah saling ketemu dan merestui hubungan kami. Terima kasih ya." Dia pun memelukku dengan senyuman dan lesung pipitnya.
***
Perkara semalam sudah membuat Lona lega sepertinya. Dan pagi ini aku menjalani kembali peranku seperti biasa. Stasiun menjadi tempatku memburu waktu. Lagi-lagi pria seperempat abad itu kembali menabrakku.
"Aduh, maaf Mba. Saya buru-buru." Wajah itu kembali terekam dan memelas.
"Oh, iya gak apa-apa." Jawabku singkat.
"Oh ya, Mba yang kemarin ya? Masih ingat Saya?" Tanyanya mengenaliku.
"Ya. Mas yang tempo hari menabrak saya juga." Sebenarnya ini hanya basa-basi saja, tentunya aku hafal betul dia yang menabrak dan menjatuhkan tas jinjingku.
"Iya Mba. Kenalkan nama saya Brian."
Ya Tuhan, adegan sinetron ini terjadi juga dalam kehidupan nyataku. "Oh ya, saya Ratna."
"Mba Ratna mau kemana?"
"Oh, saya kerja Mas Brian."
"Oh, dikirain saya mau jalan-jalan. Maaf soalnya taknampak seperti yang lainnya. Terlihat santai."
"Iya, saya selalu ganti seragam nanti di kantor."
"Oh begitu. Kalau boleh tahu Mba kerja dimana?"
"Saya kerja disalah satu bank di bilangan Jati Negara."
"Oh gitu, tunangan saya juga kerja disana Mba. Lona namanya."
Ya Tuhan, dunia ini begitu sempit. Aku baru sadar pria inilah yang aku bicarakan dengan Lona semalam. Benar namanya "Brian" aku lupa. Dari perangainya dia sopan. Sepertinya hanya miskomunikasi saja Lona.
"Mba... Mba....?" Tanyanya memecahkan lamunanku.
"Oh ya. Lona Ayunda Putri bukan?" Tanyaku penasaran.
"Iya betul, yang kerja dibagian teller."
"Kalau Lona yang itu sahabat saya. Tepatnya teman semeja kerja dengan saya." Benar sudah ini benar orangnya.
"Wah, gak nyangka ya. Bisa ketemuan di sini. Kalau begitu salam ke Lona ya." Senyumnya sambil berpamitan.
Aku pun hanya bisa melambaikan tangan perkenalan singkat itu sambil memegang smart phone-ku yang telah merekam nomor hand phone-nya. Sungguh takpercaya semua ini bisa terjadi bagai sinetron. Perkenalan nama dan diakhiri saling tukar nomor telepon.
Sesampainya di kantor aku pun mendapati sahabatku Lona sudah berseri kembali. Sudah tentu aku ceritakan perkenalan kami ke Lona. Dan pada akhirnya aku menjadi mediator atau tepatnya juru damai bagi mereka berdua di ujung smart phone-ku. Aku kini menikmati peran baru itu dengan enjoy, demi sahabat dan si pemuda penabrak, Brian.[]