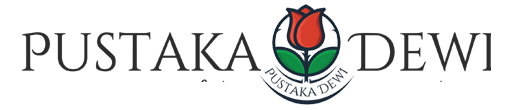Malam Itu ku susuri butanya jalan. Penerangan yang agak remang menjadi obat penunjuk arah. Ini pertama kali menginjakkan kakiku di Ibukota Periyangan. Jl. Padjadjaran begitu nama yang tertuliskan diplang depan jalan. Ku baca pelan-pelan selepas turun dari angkot berwarna orange, putih, dan hijau itu, "Pa-dja-dja-ran" itu dia namanya.
****
Supir : A, punten teu tiasa ka Dago.
Dugi ka dieu weh nyak? soal na tos wengi.
Saya : Oh, mangga Mang.
Teu sawios Mang, Hatur nuhun.
*Terjemahan
Supir : A, maaf nggak bisa ke Dago.
Sampai sini aja yah? soalnya sudah malam.
Saya : Oh, iya Mang.
Gak apa-apa mang, terimakasih.
Lantas ku bayar saja ongkos pemberangkatan dari terminal sampai ketempat aku di berhentikan. 11.55 Pm jarum jam menjerit di arloji yang ku pasang ditangan kiri.
****
Dalam perjalanan dengan keadaan yang lelah karena perjalanan jauh *menggendong ransel besar nampak seperti kura-kura berjalan, teringat masa-masa di SMA saat pelantikan Pramuka dulu. Nampaknya kondisi ku saat ini hampir sama dengan saat-saat mendebarkan itu. Hanya yang membedakan, dulu ada post-post pengujian seputar pengetahuan tentang ke-Pramukaan, baju yang ku pakai coklat-coklat plus dengan kacu dan baretnya, sekarang tak nampak itu semua.
"Waduh, ini jalan kok makin horor aja yah" keluh ku dalam perjalanan. Sepi sunyi jarang sekali nampak tanda-tanda kehidupan, yang ada hanya lambaian batang pohon lengkap dengan daun-daunnya tersapu dinginnya angin malam *wuhhhhhhhsss......... Teringat Pak Supir mengingatkan "klo sampai sini angkot jarang yang masih narik, coba jalan aja dulu sedikit sampai Jalan Merdeka disana masih banyak angkot yang ke Dago."
Sesampai ditikungan dekat stasiun Hall *Lupa nama jalannya, teringat kuliner malam yang cukup tenar *pernah masuk di televisi. "Perkedel ........."*maaf di sensor, begitu kebanyakan orang-orang mengenalnya. Entah bagaimana kronologis perkara nama kuliner itu bisa ada, yang jelas itulah namanya. Suasana Horor sekejab sirna kalah dengan kepulan asap perkedel tenar itu. "Wah, kayaknya cocok nih dingin-dingin makan yang hangat-hangat" usul ku dalam hati. Tanpa pikir panjang ku ikut ambil nomor antrian dan menunggu pesanan datang dengan apik.
Saya : Bu, Saya pesan 10 biji yah.
Ibu pedagangnya : Mangga A, sok tunggu antrian nyak.
*yang ini nampaknya tidak perlu di terjemahkan
30 menit telah berlalu, ternyata belum nampak hidangan yang di nanti datang. Pengamen bernyanyi di iringi gitar butut yang masih merdu digendongnya, mencoba menghibur aku dan para pengunjung yang menunggu giliran. Keadaan ini nampak seperti antrian pembagian sembako gratis dikampung. Pengamen ini masih setia dengan nyanyiannya walau ku dengar suaranya tak semerdu awal kali dia tampil. Sekarang agak serak-serak kering mungkin kekurangan cairan, maklum ini lagu ke-5 yang ia dendangkan.
"Nomor 31" Ibu pedagang berteriak *mengumumkan giliran, "kalau ada pengeras suara seperti mic atau semacamnya mungkin dia tak akan berteriak" pikirku dalam hati. nah, 1 nomor lagi akan sama dengan angka yang ada di kertas bekas bungkus rokok yang telah di gunting dalam genggaman ku.
Selang 2 menit kemudian "Nomor 32". Nampaknya itulah giliran ku untuk menyantap pesanan. Lelah, kedinginan sirna sudah setelah 4 biji perkedel berada didalam perut ku dan di temani segelas teh hangat tawar *perkedel yang lainnya di bungkus.
Bangkitlah aku menerusi perjalanan selepas membayar perkedel dan memberi fee ongkos nyanyian pengamen bergitar butut merdu itu.
Sesampai di per-empatan jalan yang kurang hafal namanya, aku tersentak "jalan yang ke Merdeka ke mana yah?"